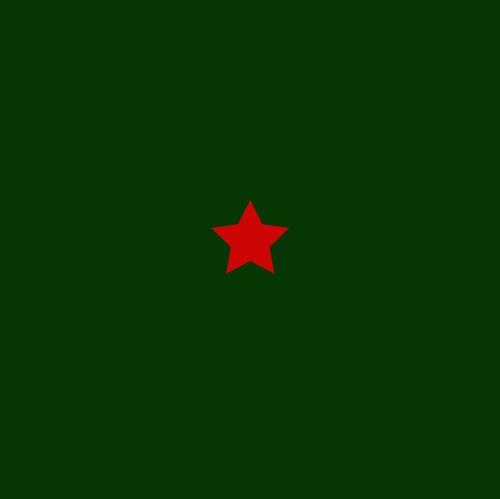Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan yang beribu kotakan Pontianak. Luas wilayah provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 km (7,53% luas Indonesia) merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Sebagian kecil dari wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau serta memiliki Danau Sentarum yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu.
Perairan di Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup tinggi untuk dikembangkan, seperti di Kepulauan Natuna, pesisir di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang, serta keberadaan Danau Sentarum. Dari kawasan perairan pesisir tersebut, masing-masing memiliki lahan konservasi yang menjadi ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, ciri khas dan keunikan tersebutlah yang mampu menjadi daya tarik wisata perairan di Kalimantan Barat.
Desa pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah pedalaman. Perbedaan tersebut tidak semata pada aspek geografis-ekologis, tetapi juga pada karakteristik ekonomi dan sosial-budaya. Secara geografis, desa pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Desa pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai (pasir atau berbatu), mangrove, estuaria, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kondisi geografis-ekologis desa pesisir mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi di dalamnya. Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan pesisir.
Aktivitas ekonomi mencakup perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. Dalam pemanfaatan yang maksimal diperlukannya pemetaan potensi melalui keterlibatan masyarakat dalam pemetaan partisipatif, guna mengetahui pemanfaatan potensi desa yang tepat dalam perencanaan pengembangan wilayah.
Pemetaan partisipatif menurut Hidayat dkk (2005) yaitu suatu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan di wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Sedangkan menurut Anonim (2003) pemetaan partisipatif adalah cara yang dapat digunakan oleh masyarakat desa atau dengan mendapat asistensi dari pihak lain, untuk mengenali kembali kondisi ruang yang sebenarnya dari suatu wilayah adat atau desa, mendokumentasikan berbagai hal yang berhubungan dengan ruang yang dibangun oleh mayarakat sendiri, menjadi alat bukti tentang klaim suatu wilayah dan bisa dibaca dengan mudah oleh pihak-pihak laindi luar desa (pemerintah, orang desa lain, perguruan tinggi dan masyarakat luas).
Lebih lanjut Anonim (2003) menyebutkan bahwa pemetaan partisipatif adalah suatu cara yang digunakan untuk mengenali kembali kondisi ruang yang sebenarnya dari suatu wilayah dan mendokumentasikan potensi sumber dayanya (hal-hal yang berkaitan dengan wilayah tersebut), yang dibuat secara bersama-sama dengan masyarakat.
Pemetaan partisipatif yang dilakukan di desa ditujukan untuk perkembangan dan perencanaan desa kedepannya, melalui pemetaan partisipatif diharapkan menjadi bagian dari transfer knowledge ke masyarakat agar pengetahuan tersebut dapat dibagikan ke berbagai elemen masyarakat.
Pengambilan data dan informasi di lapangan yang melibatkan partisipatif aktif dari masyarakat desa sebagai perencanaan dan pemberi informasi disebut sebagai pemetaan secara partisipatif. Dalam pemetaan partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat yang pada proses berlangsungnya ditentukan sendiri oleh maysarakat.
Proses pemetaan dan peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan hasil tersebut merupakan dari pengetahuan masyarakat. Pemetaan partisipatif lebih diarahkan sebagai suatu media untuk memunculkan inisiatif masyarakat memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang apa yang perlu dicatat, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempelajari lebih banyak tentang ruang kelola mereka, merupakan sebuah kesempatan untuk membuat peta menjadi lebih baik, serat merupakan media saling belajar satu sama lain.
Peta merupakan penyajian grafis bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan dan yang diwakili. Peta merupakan bidang datar dan objek yang digambarkan pada peta-peta pada umumnya terletak pada permukaan bumi, sehingga digunakan skala dan sistem proyeksi untuk menggambarkan yang sebenarnya.
Peta merupakan penyajian grafis bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan dan yang diwakili. Peta merupakan bidang datar dan objek yang digambarkan pada peta-peta pada umumnya terletak pada permukaan bumi, sehingga digunakan skala dan sistem proyeksi untuk menggambarkan yang sebenarnya.
Peta bagi masyarakat sangat penting artinya sebab dapat digunakan sebagai advokasi untuk memagari wilayahnya dari ancaman pihak luar dan media negoisasi dengan pihak luar yang berkeinginan untuk investasi dalam wilayah kelolanya, juga untuk kepentingan penyusunan kawasan (intensifikasi pertanian dan lahan) dan perubahan kebijakan pemerintah daerah. Dalam identifikasinya isu kritis dalam pembangunan desa pesisir, yang dapat terbagi ke dalam lima ranah: ekologi, sosial, ekonomi, agraria, dan geopolitik.
Pada pencapaianya diharapkan hasil dari pemetaan partisipatif menjadi formula dalam bingkai kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, energi, kesehatan, dan pendidikan.
Konsep kemandirian desa tidaklah berarti desa pesisir terlepas kesaling-tergantungannya dengan desa atau wilayah lain. Konsep kemandirian tersebut mengacu pada konsep net-benefit yang dihasilkan dari pertukaran dengan daerah lain.
Hal ini sekaligus untuk mengatasi problem surplus transfer dari desa ke kota yang selama ini terjadi. Dari hasil pemetaan partisapatif tersebut dapat didorongnya integritas kawasan perdesaan yang membangkitkan semongat gotong royong dan kerja sama antar desa.
Konsep kemandirian desa menjadi spirit dalam pembangunan berkelanjutan. aspek-aspek keberlanjutan mencakup: keberlanjutan ekologis (ecological sustainability), keberlanjutan sosial ekonomi (socioeconomic sustainability), keberlanjutan komunitas (community sustainability), dan keberlanjutan institusi (institutional sustainability). Prinsip-prinsip tersebut bisa diterapkan untuk desain pembangunan desa pesisir.
Keberlanjutan ekologis terwujud dari praktek perikanan yang tidak merusak lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang tidak melebihi daya dukung lingkungan. Kata kuncinya adalah adanya kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir untuk menjamin keberlanjutan ekologis tersebut.
Tentu, disini juga mencakup pengendalian pencemaran baik yang disebabkan limbah domestik maupun limbah industri. Karena itulah membangun desa pesisir tidak bisa berdiri sendiri karena persoalan lingkungan disebabkan juga oleh pihak supra-desa. Keberlanjutan sosial ekonomi mengacu pada tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
Keberlanjutan komunitas mengacu pada stabilitas sistem sosial, terjaminnya peran masyarakat dalam pembangunan, dan akses masyarakat pada sumberdaya baik untuk kepentingan pemanfaatan maupun pengelolaan. Sementara itu keberlanjutan institusi merupakan prasyarat bagi tercapainya tiga dimensi keberlanjutan sebelumnya.
Keberlanjutan institusi mencakup institusi politik (kapabilitas birokrasi desa), institusi sosial-ekonomi (seperti institusi keuangan desa, pasar), dan institusi sumberdaya (institusi pengelola sumberdaya). Dalam konteks pembangunan desa pesisir yang lebih spesifik dapat tercermin dari sejauh mana aturan-aturan pengelolaan sumberdaya pesisir ditegakkan dan sejauh mana kapasitas organisasi pengelola sumberdaya diperkuat. Dengan mengacu pada beberapa atribut dalam pembangunan berkelanjutan di atas, maka karakteristik desa pesisir adalah sebagai berikut :
a) mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar: pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih dan energi
b) mampu mengembangkan perencanaan desa (potensi, rencana strategis, tataruang wilayah darat dan perairan, rencana pengelolaan, rencana aksi) serta implementasinya secara dinamis dan partisipatif.
c) memiliki sistem produksi untuk mendaya-gunakan sumberdaya lokal dengan produktivitas yang tinggi dan mampu menyediakan lapangan kerja
d) masyarakatnya mampu mengorganisasi diri baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun pengelolaan sumberdaya pesisir,
e) mampu mengelola sumberdaya maupun lingkungan pesisir dan lautan serta daerah aliran sungai terkait, dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berpusat pada kekuatan masyarakat dan bersumber dari kombinasi pengetahuan lokal dan sains
f) masih terjaganya budaya dan nilai-nilai lokal yang positif yang menjadi dasar pengembangan kehidupan masyarakat
g) kapabilitas pemerintahan desa memadai untuk menggerakkan roda pembangunan desa dan mengendalikan pemanfaatan sumberdaya pesisir.
Pada prinsipnya pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk perkembangan dan perencanaan desa kedepannya dan diharapkan menjadi formula untuk terwujudnya desa yang mandiri. Kemauan masyarakat yang kuat untuk maju, dihasilnyakannya produk/karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
Pertumbuhan ekonomi dari bawah menitik beratkan pada tumbuh dan berkembangkanya sektor usaha dan industri lokal, yang mempunyai basis produksi bertumpu pada sumber daya lokal. Bentuk-bentuk usaha yang telah berkembang seperti kerajinan pertanian, perikanan, tambak, perkebunan, peternakan, industri kecil, makanan olahan sehat, adalah sektor ekonomi strategis yang harusnya digarap desa dan kerja sama desa. Lumbung ekonomi desa juga harus mengembangkan sektor usaha produksi rakyat yang mendeskripsikan kepemilikan kolektif lebih konkrit.
Bentuk-bentuk yang telah dinaungi peraturan perundangan semacam BKAD, BUMdes, dan Koperasi. Pilihan-pilihan usaha berbasis kegiatan yang telah dibentuk dan dikembangkan masyarakat desa misalnya listrik desa, desa mandiri energi, pasar desa, air bersih, usaha bersama melalui UEP, lembaga simpan pinjam, tambak ikan, dan wisata mangrove.
Hal ini dapat merujuk pada integritas kawasan perdesaan yang pada tujuannya untuk menjahit kawasan-kawasan desa untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan atau pemanfatan potensi desa yang telah dipetakan melalui pemetaan partisaptif itu sendiri. Melalui profil desa yang dihasilkan dari pemetaan partisipatif diharapkan menjadi bahan analisis untuk mengetahui potensi, permasalahan, dan menentukan tata guna kelola sumber daya alam.
Pendampingan yang dilakukan secara berkala dan intensif diharapkan melatih masyarakat agar mampu untuk belajar mengelola kegiatan pembangunan secara mandiri. Berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas diberikan oleh pendamping kepada masyarakat desa. Pengembangan kapasitas di Desa dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian proses belajar sosial.
Dalam bangunan kerangka pikir pemberdayaan masyarakat desa, penerapan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa ini harus dikawal oleh tenaga profesional yang bertugas mensosialisasikannya kepada masyarakat desa.
Pendampingan dan pelatihan dari pendamping kepada masyarakat desa ini diharapkan mempercepat proses internalisasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai sebuah proses pembiasaan sosial dalam diri masyarakat desa.
Selain itu, tenaga pendamping profesional juga bertugas mendampingi warga desa meningkatkan daya tawar dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan masyarakat desa sehingga program dan kegiatan pembangunan mampu dikelola masyarakat desa itu sendiri.
Tenaga Pendamping profesional bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja pendampingan desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial.
Dengan demikian, pendamping tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa.
Kerja Pendampingan bukanlah melakukan kontrol dan mobilisasi partisipasi terhadap warga desa dalam rangka menjalankan prosedur-prosedur kerja yang serba dirancang dari kepentingan luar desa.
Kerja pendampingan lebih tepat dimaknai sebagai proses fasilitasi terhadap warga desa agar berdaya dalam memperkuat desanya sebagai komunitas yang memiliki pemerintahannya sendiri (self governing community).
Nurmanto (Tim Asistensi Sosial Pemetaan Partisipatif)
Untuk mendownload aplikasinya bisa ke Play Store